BincangMuslimah.Com – Perkawinan paksa yang ditentukan oleh orangtua atau wali tanpa mempertimbangkan suara perempuan dahulu sering kali terjadi. Orang-orang gemar menamainya dengan sebutan perkawinan paksa. Saat ini, mungkin sudah mulai meninggalkan tren kawin paksa. Beberapa di antara kita mungkin hanya menemukan kasus ini di dalam bacaan novel atau drama di dalam layar kaca. Namun nyatanya, sedikit banyak perkawinan paksa masih saja ada.
Kawin paksa masih dijumpai meski seringkali tertutup, tenggelam lalu menghilang begitu saja. Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) ini misalnya. Humas Pengadilan Agama Kabupaten Gunung Kidul mengatakan jika pada tahun 2018 ada 4 pasangan yang mengalami nikah paksa dan satu pasang di tahun 2019. Kelima pasangan itu pada akhirnya memilih bercerai karena rumah tangga mereka sering dihiasi dengan percekcokan.
Pada tahun 2019 Komnas Perempuan mendapatkan laporan dari Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Provinsi Riau jika ada dua kasus perkawinan paksa. Laporan yang diadukan pada lembaga UPTD PPA itu berakhir dengan tindakan dalam bentuk pendampingan psikologis pada orang tua
Sesungguhnya perkawinan paksa bisa berdampak pada laki-laki mau pun perempuan. Namun perempuan yang paling sering menjadi korban dalam praktik paling perkawinan paksa. Hal ini karena adanya stigma bahwa perempuan tidak punya kuasa atas diri sendiri. Keberadaan perempuan sebelum menikah di tanggung oleh sang ayah. Dan setelah menikah, ‘tanggung jawab’ tadi berpindah kepada suami.
Sudut Pandang Hukum
Komnas Perempuan sendiri telah menentukan sikap terkait persoalan perkawinan paksa. Dalam Catatan Tahunan (Catahu) Komnas Perempuan 2020, perkawinan paksa merupakan salah satu bentuk kekerasan seksual. Ada beberapa hal yang Komnas Perempuan lihat dalam mengidentifikasi praktik perkawinan paksa. Pertama saat anak tidak punya pilihan lain selain mengikuti kehendak orangtua untuk menikah dengan seseorang yang tidak ia suka bahkan tidak kenal.
Kedua, praktik perkawinan paksa kerap terjadi pada korban pemerkosaan. Korban justru dinikahkan dengan pelaku yang seharusnya diadili dengan tujuan untuk mengurangi aib keluarga. Ketiga, praktik cerai gantung di mana saat perempuan mengajukan gugat cerai karena alasan yang kuat, permintaan tersebut tidak dikabulkan bahkan dipersulit. Memaksa perempuan untuk tetap terus terikat dengan ikatan pernikahan yang tidak mereka inginkan.
Indonesia sebagai negara hukum sesungguhnya telah mengatur tentang persoalan ini. Semuanya telah tercantum di dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Pada pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa perkawinan harus mendapat persetujuan oleh kedua belah yang terlibat dalam perkawinan tanpa paksaan dari mana pun.
Sanksi Penyalahgunaan Otoritas
Kalau tetap melaksanakn perkawinan, maka dapat membatalkannya sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang tentang Perkawinan. Di dalam peraturan tersebut, dapat membatalkan pernikahan jika mempelai tetap melaksanakan dalam paksaan dan ancaman.
Pemerintah juga telah menyiapkan sanksi bagi orang-orang yang menyalahgunakan otoritasnya sebagai orangtua atau wali untuk melaksanakan kawin paksa. Hal ini tercantum di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KHUP) Pasal 335. “Barang siapa melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan, sesuatu yang tidak menyenangkan baik terhadap orang itu sendiri mau pun orang lain, maka akan mendapat ancaman pidana minimal satu tahun penjara.”
Pembatalan perkawinan paksa dapat terjadi setelah hakim mengabulkan. Namun keputusan itu menjadi tidak berlaku jika di dalam perkawinan tersebut terdapat beberapa hal yang tercantum di dalam Pasal 28 ayat (2) tentang Undang-Undang Perkawinan. Yaitu anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut dan suami istri tersebut mempunyai itikad baik.
Sudut Pandang Islam
Sebagian orang berdalih, menggunakan agama sebagai landasan. Pandangan yang menyatakan bahwa perempuan tidak berhak menentukan pilihan terhadap pasangannya juga mendukung hal ini. Semua telah ayah tentukan atau wali yang menggantikannya, jadi seperti tidak lagi membutuhkan kerelaan.
Dasar pemikiran ini mungkin dengan adanya istilah hak ijbar pada ayah atau wali dari perempuan. Orang yang mendapat hak ijibar punya kuasa untuk menikahkan anak perempuannya. Keberadaan hak ijibar ini sebenarnya adalah bentuk tanggung jawab dari ayah dan memiliki tujuan untuk memberikan perlindungan kepada anaknya.
Persyaratan Hak Ijbar
Sebagian orang kerap kali menyalahgunakan hak ijibar dan menganggap sebagai bentuk kekuasaan untuk mengendalikan pernikahan. Padahal sebenarnya hak ijibar merupakan bentuk wewenang ayah atau wali untuk menikahkan anak perempuannya tanpa ada paksaan dengan mempertimbangkan kerelaan sang anak.
Mazhab Syafi’i mematok beberapa persyaratan dari hak ijibar ini. Pertama, pelaksanaan pernikahan dengan syarat tidak ada kebencian dari kedua mempelai. Kedua, di dalam pernikahan tidak ada konflik atau selisih paham antara anak perempuan dengan ayahnya. Ketiga, calon suami harus setara (kufu’). Keempat, mengharuskan mas kawin tidak kurang dengan mas kawin pada umumnya. Dan yang terakhir, memastikan calon mempelai laki-laki tidak akan menyakiti mempelai perempuan setelah menikah nanti.
Jelas sudah jika tiga dari lima syarat yang dalam Mazhab Syafi’i ini benar-benar memperhitungkan kerelaan dari mempelai perempuan. Pernikahan secara paksa tidak selalu menimbulkan rasa suka sama suka dan akhir yang bahagia. Beberapa yang membangun rumah tangga dari paksaan terkadang bermuara pada kekerasan, kebencian lalu perceraian.
Hal ini justru bertentangan dengan syarat pertama dan kelima. Ketika dalam pernikahan terindikasi tidak adanya kerelaan dari calon mempelai perempuan, sudah akan ada perselisihan antara anak perempuan dengan sang ayah. Dan ini bertentangan dengan syarat ke dua yang mengharuskan tidak ada permusuhan di antara keduanya.
Dalam buku Fiqh Perempuan karya K.H Muhammad Husein, Dr. Wahbah az-Zuhaili pernah mengutip pendapat ulama mazhab Fiqh soal kawin paksa. Ia berkata bahwa sebuah perkawinan tidak akan sah jika dari kedua mempelai tidak ada kerelaan. Jika ada pemaksaan dengan mengancam keselamatan jiwa (ikrah) maka akad nikah akan berubah menjadi rusak (fasad).
Bagaimana mengukur kerelaan siap menikah dari mempelai perempuan? Menurut Abu Hanifah, hal ini bisa terlihat dari kedewasaan (baligh) tanpa melihat apa status atau golongan dari perempuan tersebut. Kedewasaan seseorang pada umumnya terlihat dari bagaimana dia menanggapi persoalan dan cerdas dalam mengambil keputusan. Bagaimana pergaulan dan moralitas dalam kehidupan sosial juga mendukung semua hal.
Jika beberapa indikasi itu telah nampak dari calon mempelai perempuan maka ia berhak untuk bersuara atas diri sendiri. Apakah akan tetap melanjutkan perkawinan dengan mewakilkan akad kepada orang lain (di sini adalah ayah atau wali) atau memutuskan untuk tidak menikah.
Rekomendasi









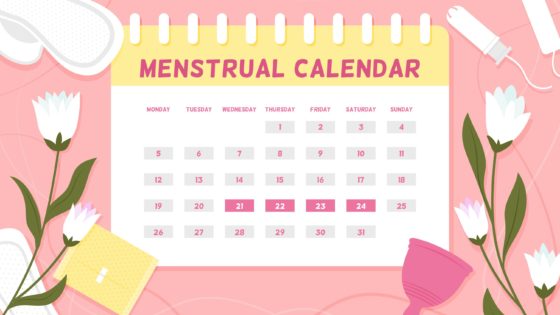

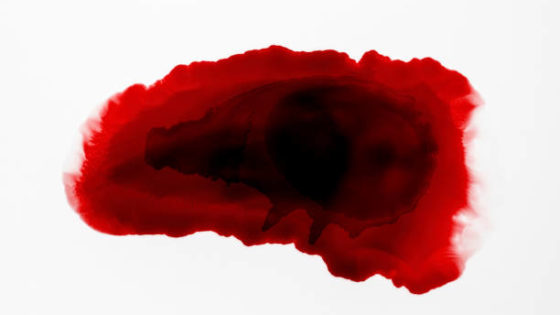




1 Comment