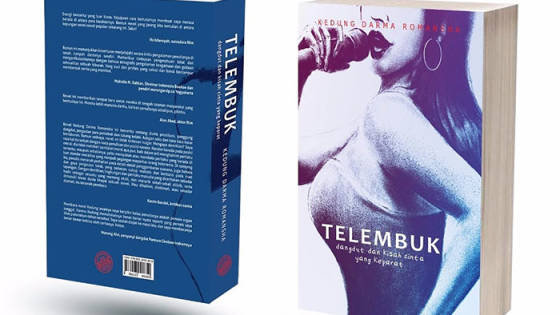BincangMuslimah.Com – Hampir semua doktrin-doktrin keagamaan ditulis oleh laki-laki dengan menggunakan prespektif mereka. Sehingga, pengalaman perempuan belum terakomodasi dengan baik. Demikianlah penyampaian Bapak Imam Nahe’i dalam pelatihan kepenulisan keislaman berbasis gender oleh Bincang Muslimah Sabtu lalu (29/8).
Oleh karena itu, Bapak Imam Nahe’i berpesan kepada para penulis Bincang Muslimah agar menghadirkan kembali pengalaman dan peran perempuan di dalam tulisan-tulisan yang berkaitan dengan keislaman. Menurutnya, ketidak hadiran pengalaman perempuan di dalam sebuah tulisan akan menyebabkan bahasa tulisan tersebut dapat berdampak diskriminasi terhadap perempuan.
Salah satu ayat yang menjadi argumen Bapak Imam Nahe’i tentang pentingnya menghadirkan pengalaman perempuan dalam menulis adalah ayat haid. Allah swt. berfirman, Yas alunaka anil mahidh (mereka bertanya kepadamu tentang mahidh). Allah swt. menggunakan kata mahidh bukan haid. Mahidh berarti darah haid, sedangkan haidh adalah orang yang sedang haid. Allah memilih mahidh bukan haidh karena berangkat dari pengalaman perempuan.
Mengubah Pengalaman Perempuan Jahiliyah Bahasa
Pada zaman jahiliyah, tidak mengajak perempuan haid makan bersama. Tidak mengajak perempuan minum bersama. Tidak pula mengajak mereka bicara dan duduk bersama. Perempuan-perempuan yang haid pada masa itu berada di kandang belakang rumah untuk menjalankan fungsi reproduksinya itu. Bahkan, konon perempuan-perempuan yang baru selesai haid ketika itu baunya sangat menyengat.
Pengalaman perempuan tersebut ingin dirubah dengan kekuatan bahasa, maka Allah swt. menggunakan lafadz mahidh/darah haid. Allah swt. menegaskan bahwa yang bermasalah itu darah haidnya bukan haidnya/orangnya.
Orang haid itu manusia seutuhnya yang sedang menjalankan fungsi reproduksi dan tidak ada yang salah dalam dirinya. Kemanusiaannya tidak turun karena dia menjalankan fungsi reproduksi. Maka, Al-Qur’an menggunakan redaksi mahidh untuk mengubah cara pandang masyarakat jahiliyah yang mempermasalahkan kemanusiaan orang haid.
Begitu pula penggunaan bahasa pada kelanjutan ayat tersebut. Allah swt. berfirman, fa’tazilun nisaa a fil mahidh. Dalam ayat ini, Allah menggunakan kata fa’tazilu (hendaknya laki-laki yang berisolasi diri). Allah swt. bukan menggunakan kata fa’ziluu (hendaknya mengasingkan perempuan).
Hal tersebut juga ingin memotret pengalaman perempuan di masa Jahiliyah. Mereka menjalankan fungsi reproduksinya dengan diasingkan dari keluarga. Al-Qur’an mengatakan jangan lakukan i’zilu tapi fa’taziluu. Kamu yang berisolasi, jangan perempuan yang kamu keluarkan.
I’zilu tidak sama dengan fisik dan berbeda dengan hujran yang berarti meninggalkan. I’tazilu bisa dalam satu kamar tetapi satunya menghadap ke samping satunya menghadap ke samping lainnya atau tidak melakukan hubungan badan.
Selanjutnya firman Allah swt. wa laa taqrabuuhunna hatta yathhurna. Redaksi yang digunakan Al-Qur’an tersebut juga menarik. Ia menggunakan kata thahura, tathhir, tathahhur dan seterusnya. Hal ini ingin menunjukkan kemanusiaan perempuan. Ketika mereka sedang menjalankan fungsi reproduksi, mereka hanya mengalami hambatan kesucian seperti laki-laki pada umumnya kalau kencing atau BAB yang juga mengalami hambatan kesucian.
Menafsirkan Al-Quran dan Hadis dengan Melihat Pengalaman Perempuan
Bapak Imam Nahe’i juga menyinggung hadis yang menjadi streotip bagi perempuan; al mar’atu naqisatu aqlin wa diinin. Perempuan itu kurang akal dan agamanya. Jika membacanya tanpa melihat pengalaman perempuan ketika muncul hadis ini, maka akan salah menangkap pesan.
Pada saat itu, perempuan tidak mendapatkan hak dan pendidikan yang setara dengan laki-laki. Maka, perempuan tidak mendapatkan akses yang setara untuk menimba ilmu sebagaimana laki-laki. Perempuan tidak mendapat ruang yang cukup dan suami dan keluarganya untuk mendapatkan akses yang sama dengan laki-laki. Merekapun terbentuk secara budaya tidak mendapatkan kemampuan yang sama dengan kemampuan laki-laki karena aksesnya berbeda.
Dengan demikian, maka ketika hendak menulis atau menafsirkan teks agama harus memperhatikan dua hal. Pertama; pengalaman perempuan di mana teks itu turun. Kedua, pengalaman perempuan di mana teks itu akan diaplikasikan atau dibumikan. Ketika memperhatikan dua hal tersebut, maka insya Allah tidak ada lagi diskriminasi dan pengabaian peran perempuan dalam penafsiran teks agama.
Bapak Imam Nahe’i memungkasi materinya dengan mengatakan bahwa ketika menulis sebuah gagasan tentang isu perempuan, maka catatannya satu, harus mengkaji situasi dan pengalaman perempuan. Wa Allahu a’lam bis shawab.