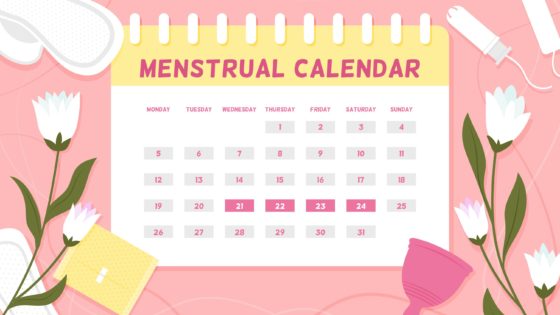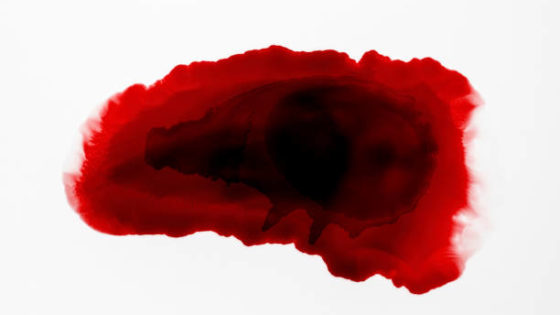BincangMuslimah.Com – Qasim Amin adalah seorang emansipator Mesir yang mungkin zaman sekarang kurang banyak diperbincangkan. Namun pada abad 19 di Mesir, emansipasi perempuan yang digaungkan Qasim Amin merupakan perspektif yang banyak menimbulkan perdebatan di kalangan masyarakat dan akademisi kala itu.
Dalam banyak pendapat beliau disebut berguru kepada Muhammad Abduh. Qasim Amin dilahirkan di kota Iskandaria Mesir 1 Desember 1863 M, dari seorang ayah keturunan Turki Utsmani bernama Muhammad Bik Amin Khan.
Di Mesir, ayahnya menjabat Gubernur di Kurdistan dan ibunya adalah putri dari Ahmad Bik Khattab yang berdarah asli Mesir dan merupakan keluarga dari Muhammad Ali Pasha. Pada 1875, Qasim menamatkan Sekolah dasar istimewa di Raksu al-Tyn di pusat kota Alexandria. Pada tahun 1881, Qasim meraih gelar licance dari fakultas Hukum dan Administrasi di sebuah sekolah kota Khedival.
Karena kecerdasannya, Qasim Amin kemudian mendapat kesempatan untuk melanjutkan studi ke Fakultas Hukum Universitas Montpellier di Paris Perancis. Setelah itu, Qasim Amin bekerja di Dewan Perwakilan Rakyat dan sebuah lembaga hukum. Ia menetap di Kairo hingga wafatnya 22 April 1908.
Karya-karyanya yang banyak menggugah semangat perempuan untuk bangkit adalah Tahrir al-Mar’ah (1900) dan al-Mar’ah al-Jadidah (1911). Dua karya inilah yang kemudian banyak memberi inspirasi kepada para feminis Muslim untuk memperjuangkan kebebasan perempuan setelahnya hingga sekarang.
Qasim Amin merupakan tokoh feminis Muslim pertama yang memunculkan gagasan tentang emansipasi perempuan Muslim melalui karya-karyanya. Qasim Amin memunculkan gagasannya didasari oleh keterbelakangan umat Islam yang menurutnya disebabkan oleh pandangan dan perlakuan yang salah terhadap perempuan.
Pendapat yang berkembang bahwa setiap pemikir ialah produk pada zamannya. Ini dimaknai bahwa gagasan-gagasan atau ide dasarnya adalah pengalaman dan hasil interaksi antara pemikir dan lingkungan sosio-historis di sekelilingnya.
Dalam sebuah karyanya Sejarah Penindasan Wanita, Qasim menyatakan, “dari waktu lahir hingga mati, perempuan adalah budak, sebab dia tidak hidup oleh atau untuk dirinya sendiri. Perempuan hidup terus dan untuk pria, bergantung pada pria dari semua apa yang dibutuhkanya. Perempuan meninggalkan rumah hanya jika ia dikawal oleh pria, ia bepergian hanya dibawah pandangan pria, mendengar hanya dengan telinga pria, berkeinginan hanya saat pria mengizinkannya, dan dapat membuat pertentangan kecuali pria memerintahnya. Perempuan tidak dapat dianggap sebagai seorang yang independen. Ia hanya sebagai anggota badan pria”.
Berangkat dari inilah lahir pemikiran emansipasi Qasim Amin. Gagasannya mengenai emansipasi menjadi kontroversi di kalangan ulama Mesir kala itu. Meskipun ide Qasim Amin ini mendapat banyak sorotan dari para ulama Al-Azhar, ia tidak pernah berhenti untuk menyuarakannya.
Gagasan emansipasi bertujuan untuk membebaskan kaum perempuan sehingga mereka memiliki kebebasan dalam berpikir, berekpresi, berkehendak, dan beraktivitas sebatas yang dibenarkan oleh ajaran Islam dan mampu memelihara standar moral masyarakat.
Kebebasan dapat menggiring manusia untuk maju dan bergerak pada kebahagiaan. Tidak seorang pun dapat menyerahkan kehendaknya kepada orang lain, kecuali dalam keadaan sakit jiwa dan masih anak-anak. Karena itulah ia menyarankan adanya perubahan, karena menurutnya tanpa perubahan mustahil kemajuan dapat dicapai.
Qasim Amin memaparkan tiga gagasan tentang emansipasi perempuan yakni:
1. Pentingnya Pendidikan bagi Perempuan dan Relasinya dengan tugas Rumah Tangga.
Qasim Amin menyatakan bahwa pendidikan perempuan adalah jalan untuk membebaskan kaum perempuan dari praktik marginalisasi dan subordinasi yang mengekang mereka. Adanya pendidikan perempuan dapat meningkatkan perannya dalam ranah domestik. Selain perannya sebagai pendidik anak, mitra dialog dengan suami dan juga bidang kemasyarakatan.
Lebih lanjut, jika perempuan Mesir terus-menerus dibiarkan tanpa pendidikan, ini akan menjadikan mereka seperti tersimpan dalam kotak dan hanya dilihat sebagai hiasan tanpa adanya pengembangan dan sangat tidak bermanfaat bagi Mesir. Seorang perempuan dapat hidup dengan baik jika dibekali ilmu pengetahuan. (Qasim Amin, al-Mar’ah al-Jadidah:167)
2. Perempuan dan Hijab
Perintah hijab yang disyariatkan mencakup tiga tingkatan menurut kadar ketertutupannya yang didasarkan pada dalil al-Qur’an dan Sunnah Nabi, salah satunya ialah hijab berarti dibatasi olen dinding dan ruangan khusus bagi wanita. Baik dirinya sendiri, pakaian, perhiasan luar perhiasan batin, maupun wajah, telapak tangan, dan anggota badan lainnya tidak terlihat. Hal ini dapat dilihat pada surat al-Ahzab (33):53 (Yunus, 1987).
Dalil ini menunjukkan bahwa pertanyaan atau permintaan apa pun kepada mereka (para isteri Nabi SAW) hendaknya dilakukan dari balik hijab, sehingga baik laki-laki maupun perempuan tidak dapat saling melihat. Jadi, dengan turunnya ayat ini menetapkan dan menguatkan perintah tersebut.
Namun menurut Amin cara berpakaian kaum perempuan yang menutup seluruh tubuh merupakan adat istiadat yang menjadi penghalang kemajuan perempuan. Cara berpakaian yang demikian mereka namakan hijab. Menurutnya cara berpakaian ini tidak berdasarkan dalil agama, al-Qur’an dan Hadist. Tidak terdapat di dalam al-Qur’an dan Hadist ajaran yang mengatakan bahwa wajah perempuan merupakan aurat dan karena itu harus ditutup .
Amin memandang hijab sebagai satu nilai tata kesopanan yang perlu dilestarikan dan mengenai hijab yang berlaku di Mesir tidak sesuai dengan syari’at Islam. Dalam tradisi masyarakat Mesir pada saat itu, hijab dimaknai sebagai kewajiban perempuan untuk menutup seluruh tubuh termasuk muka dan telapak tangan dengan pakaian khas dan mengurung serta menutup diri dari masyarakat.
Hal ini berarti bahwa satu-satunya peran gender dan kodrat alamiah perempuan ialah dengan tetap tinggal atau tinggal di rumah. Gagasan Amin dalam masalah hijab yang bertentangan dengan pendapat para ulama saat itu, bukanlah hal yang mutlak. Namun adalah anggapan yang menyatakan bahwa, idenya yang bertentangan dengan Nash al-Qur’an tersebut yang perlu dibahas.
3. Masalah perkawinan dan perceraian.
Amin menentang kebiasaan yang berlaku di Mesir saat itu, melarang perempuan untuk menentukan sendiri jodohnya sehingga ia cenderung diperlakukan sebagai benda mati. Kebiasaan tersebut didukung oleh segala lapisan, baik golongan awam maupun kelompok cendekiawan dan ulama fiqh pada umumnya. Kekeliruan tersebut menurutnya berlandaskan pada analisis terhadap defenisi-defenisi yang terdapat pada kitab-kitab fiqh.
Dalam kitab tersebut digambarkan bahwa suatu perkawinan hanya terletak pada keperempuanan secara biologis, dan tidak digambarkan tujuan yang lebih bermakna dan sakral yang ingin dicapai dalam suatu perkawinan. Padahal dalam surat ar-Rum (30): 21 menjelaskan bahwa tujuan dari sebuah perkawinan adalah untuk menegakkan dasar sakinah mawaddah wa rahmah.
Hukum perceraian menurutnya adalah haram. Sebagai seorang ahli hukum, ia ingin untuk meninjau kembali sistem perceraian yang tidak adil tersebut. Dalam upaya memperkecil angka perceraian, ia mengusulkan kepada pemerintah sebuah rancangan aturan perceraian yang terdiri dari lima pasal yang menurutnya tidak bertentangan dengan al-Qur’an. (Qasim Amin, Sejarah Penindasan Wanita:165)