BincangMuslimah.Com – Istimewa, satu kata bagi perempuan. Alasannya sederhana, seorang perempuan senantiasa mampu melawan banyak hal dalam hidup. Sejak lahir, perempuan menjadi pihak yang dilemahkan, dianggap tak bisa melakukan banyak hal terutama pekerjaan-pekerjaan kasar yang membutuhkan tenaga lebih. Akhirnya, banyak keluarga lebih bersyukur jika yang lahir adalah anak laki-laki ketimbang perempuan.
Sulitnya Menjadi Perempuan
Dalam lingkungan rumah, perempuan dibiasakan melakukan pekerjaan rumah. Pekerjaan rumah pun dianggap sebagai pekerjaan wajib bagi perempuan. Padahal, menjaga kebersihan dan kerapian rumah adalah kewajiban semua penghuni, baik laki-laki maupun perempuan, keduanya punya kewajiban untuk menjaga kebersihan dan mengatur kerapiannya.
Di lingkungan sekolah, perempuan juga menghadapi kesulitan. Karena merasa punya power, banyak murid laki-laki yang menganggu. Ada yang sekadar menggoda dengan cat calling, menjawil bagian tubuh, melontarkan kata tak senonoh, bahkan ada yang sampai membuka rok. Belum lagi menghadapi para guru lelaki yang sangat mendominasi dan merasa berhak atas tubuh perempuan. Paling parah, menghadapi guru perempuan yang menyalahkan murid perempuannya karena misalkan rok kecilnya disibak murid lelaki lantaran tidak memakai rok panjang.
Padahal, persoalan panjang-pendeknya pakaian, apalagi masih anak-anak, bukanlah sebuah masalah. Yang perlu diperhatikan adalah pergaulan para murid lelaki. Pelecehan seksual harus diajarkan sejak dini. Inilah pentingnya sex education, agar sejak kecil tidak tertanam dalam diri anak perempuan bahwa laki-laki boleh melakukan apa saja padanya dan tak bisa melawan. Juga sebaliknya, lelaki sudah semestinya menghormati atau menghargai perempuan sebagai sesama manusia, bukan malah melecehkannya.
Tak berhenti sampai di situ. Beranjak dewasa, perempuan akan menghadapi masalah yang jauh lebih kompleks. Cat calling di jalan, ancaman diperkosa bukan hanya oleh orang yang tak dikenal tapi juga oleh orang terdekat, tidak boleh melakukan ini-itu hanya karena berjenis kelamin perempuan, bahkan tak didukung meraih cita-citanya oleh keluarga dan dipaksa menjadi pribadi yang sesuai dengan keinginan keluarga.
Cita-cita: Nyawa Hidup Perempuan
Ada dua pertanyaan mendasar mesti kita jawab dalam hidup. Pertama: Siapa aku? Kedua: Hidup ini untuk apa?
Untuk menjawab dua pertanyaan ini, butuh perenungan panjang juga perjalanan hidup yang tak mulus. Sedih, suka, luka, bahagia, turut mengiringi menuju jawabannya. Dua pertanyaan ini mendorong perempuan mengenali dirinya sendiri. Misalnya dengan menemukan passion dalam hidup, menentukan tujuan hidup, bahkan bisa saja dengan memutuskan untuk menjalankan hidup yang seperti apa, menjadi apa, dan menjalankan hidup dengan bagaimana. Semua bisa dicapai dengan mewujudkan cita-cita.
Sayangnya, ada banyak perempuan yang stuck dengan apa yang mereka impikan. Banyak perempuan melepas profesi idaman lantaran keluarga melarangnya. Banyak perempuan membuang jauh-jauh cita-citanya dan memutuskan menghabiskan sepenuh hidupnya sebagai ibu rumah tangga. Bahkan ada yang tak menjadi diri sendiri demi menyenangkan keluarga.
Menjadi IRT Bukan Penghalang
Memilih menjadi ibu rumah tangga full time seharusnya tak mesti membuang cita-cita. Ibarat sebuah rumah, cita-cita adalah bangunan permanen di mana perempuan akan bermukim seumur hidupnya. Untuk itu, perlu membangun fondasi terlebih dahulu. Sebelum menjadi seorang ibu, wajib bagi perempuan untuk “menemukan siapa diri sendiri”. Ajeg. Sudah menjadi orang, bukan sekadar manusia.
Perjalanan menemukan diri memang tak mudah. Prosesnya sangat panjang dan manis-pahit kadang tak bisa terbendung. Banyak perempuan memilih menyerah dan menikah. Setelah menikah, apa yang telah mereka bangun—lantaran tidak kokoh—akhirnya roboh. Cita-cita tak terwujud. Menjadi ibu rumah tangga menjadi satu-satunya pilihan.
Untuk menyiasati himpitan situasi ini, perempuan perlu menempa diri dengan tekun. Jika bercita-cita menjadi dosen, maka harus studi dan menghabiskan waktu bertahun-tahun. Perempuan boleh menunda pernikahan sampai menjadi dosen. Setelah itu, barulah perempuan bisa menikah dan punya anak. Juga menyeimbangkan kehidupan rumah tangga dan karir bisa.
Lantaran banyak perempuan yang bisa mengerjakan banyak hal, sebenarnya melanjutkan studi sembari berkeluarga pun tak apa-apa. Untuk kasus ini, perempuan butuh energi lebih. Sudah banyak perempuan yang telah menjalani dan membuktikan. Meskipun pada akhirnya, lagi dan lagi, mereka terkungkung dalam stigma: “Perempuan itu lebih baik mengurus anak dan suami di dalam rumah saja, tidak usah repot-repot bekerja”.
Kita mafhum, memang ada perempuan yang memilih menjadi ibu rumah tangga saja. Tapi, berkeluarga sekaligus bekerja juga salah satu jalan hidup yang bisa perempuan pilih.
Stigma Bukan Hambatan
Dominasi laki-laki atas perempuan memang menyebalkan. Tapi, perempuan yang nyinyir dengan kehidupan perempuan lain pun tak kalah menyebalkan. Ada seorang ibu rumah tangga yang menyerang seorang ibu yang bekerja. Ada pula ibu yang bekerja menyerang ibu rumah tangga. Padahal, semua hanya soal pilihan. Setiap orang berhak memilih jalan hidupnya dan sebagai sesama perempuan seharusnya saling mendukung, bukan malah merundung.
Kebiasaan saling menyerang ini tidak muncul begitu saja. Ada satu akar yang menumbuhkan sikap, buah dari kebencian ini. Salah satu penguat akar tersebut adalah stigma. Stigma-stigma yang melekat dalam diri perempuan sebenarnya sangat tidak rasional.
Pertama, stigma bahwa perempuan yang bekerja tidak akan becus mengurus anaknya. Stigma ini melekat hingga saat ini, zaman di mana sudah bisa mengerjakan banyak pekerjaan dari dalam rumah, tanpa perlu bolak-balik kantor selama lima atau enam hari dalam seminggu dari pagi hingga sore bahkan malam hari. Perempuan bisa membagi waktunya sebagai ibu rumah tangga dan menjadi pekerja di dalam rumah. Zaman sudah bergerak, stigma semacam ini seharusnya sudah tak relevan.
Kedua, stigma bahwa istri dengan gaji lebih besar atau karir lebih tinggi ketimbang suaminya akan membuat rumah tangga hancur berantakan. Ada satu hal yang luput di sini: kerjasama. Penting mengimplementasikan kesetaraan dalam sebuah relasi atau hubungan. Jika ikatan pernikahan hanya berlandas dominasi, setiap hal sudah pasti tak beres lantaran rasa takut selalu menyisipi. Hubungan yang baik harus berlandaskan kerjasama, bukan rasa takut.
Ketiga, stigma bahwa perempuan yang terlalu pintar, laki-laki akan menghindarinya. Tidak ada ukuran pasti dari istilah “terlalu pintar”. Perempuan pintar tidak perlu bersusah payah mencari laki-laki yang lebih pintar. Menjadi teman hidup adalah soal melengkapi, bukan saling merebut kendali. Kecocokan jadi ukuran, bukan kepintaran.
Tantangan Perempuan
Tiga stigma yang di atas adalah sebagian kecil dari banyak stigma yang melekat dalam diri perempuan. Ketidakadilan yang perempuan alami karena konstruksi sosial, budaya dan agama sangat bisa untuk mengubahnya menjadi kekuatan. Kekuatan untuk membuktikan pada dunia, perempuan bukan makhluk yang lemah, bukan sekadar objek bagi laki-laki, bukan pula tidak sejajar dengan laki-laki. Baik laki-laki dan perempuan, keduanya sama-sama manusia. Tak ada yang membedakan kecuali kualitas diri masing-masing.
Zaman bergerak. Segala sesuatu semakin canggih. Kini, tugas perempuan bukan hanya menghilangkan dominasi laki-laki. Lebih berat ketimbang itu, perempuan mesti mengatur strategi menghadapi zaman baru, berpikir jauh ke depan, dan melakukan tindakan nyata. Salah satunya adalah dengan mewujudkan cita-cita dan membuang jauh semua stigma. Menjadi bagian dari pertumbuhan peradaban di dunia.

















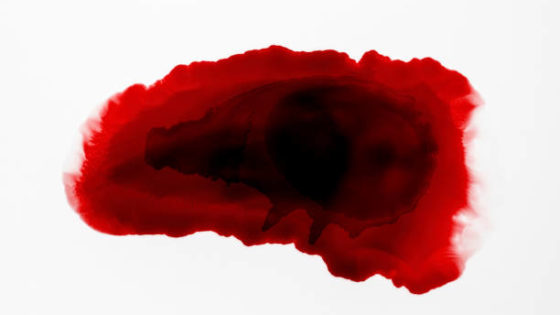

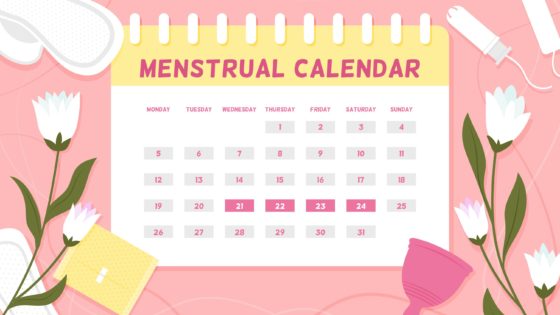

3 Comments