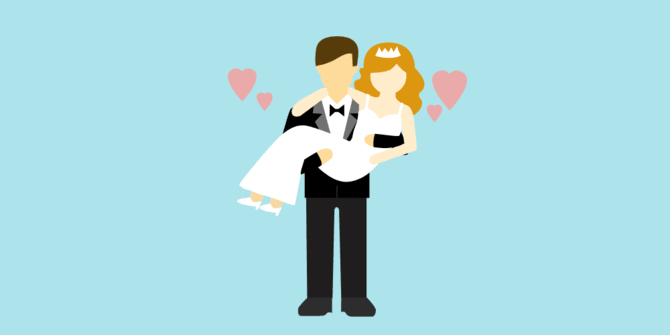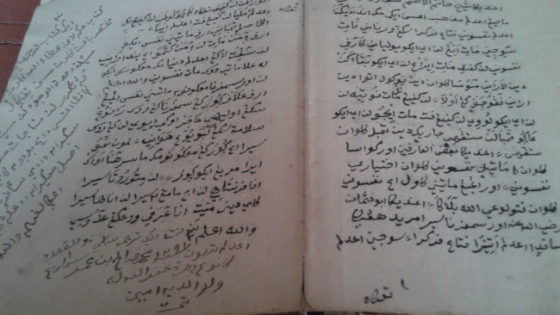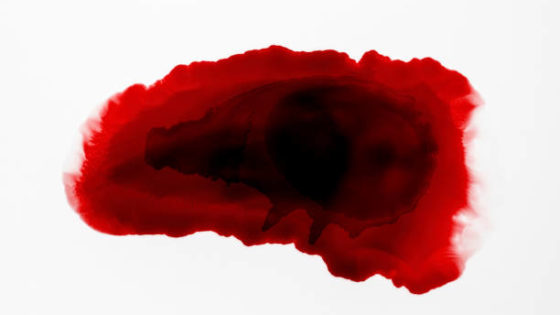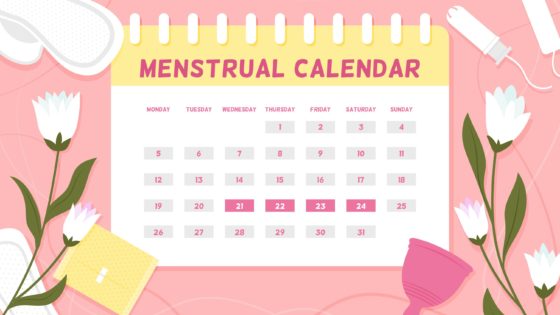BincangMuslimah.Com – Perjuangan penghapusan perkawinan anak telah berlangsung lebih dari satu abad. Legitimasi pelarangan perkawinan anak telah ada berupa undang-undang. Sangat disayangkan, hingga saat ini masih ada yang mempromosikan kawin anak dan dinilai sangat membawa mudarat. Beberapa waktu lalu, media social dihebohkan dengan promosi perkawinan anak disebuah situs daring.
Dalam situs tersebut terdapat narasi persuasif menikah pada usia 12-21 tahun dan orangtua sangat dianjurkan menikahkan anaknya pada usia tersebut. Situs Aisha Wedding begitu namanya itu juga menganjurkan nikah siri dan poligami. Promosi yang secara terang-terangan jelas sangat bertentangan dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah direvisi menjadi UU Nomor 16 tahun 2019 dan UU Nomor 35 Tahun 2014. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 telah mengubah batas minimal usia melakukan perkawinan pada UU Nomor 1 Tahun 1974 dari 16 tahun menjadi 19 tahun bagi perempuan.
Dikutip dari Faqihuddin Abdul Kodir dari Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) dalam sebuah webinar pecan lalu, menanggapi promosi kawin anak tersebut merupakan sebuah tamparan bagi semua baik pemerintah dan KUPI. Beliau juga menambahkan bahwa dalam Undang-undang Perlindungan Anak telah dijelaskan bahwa segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
Seperti yang telah dijelaskan diatas, pertanyaan yang muncul adalah apakah Undang-Undang Perkawinan telah efektif dalam mengurangi angka perkawinan anak dan apakah Undang-undang Perkawinan tersebut relevan untuk saat ini? Secara jelas tentunya belum!
Setelah Undang-Undang Perkawinan, dikutip dari buku Status Wanita di Asia Tenggara yang ditulis oleh Khoiruddin Nasution dijelaskan bahwa dilakukan upaya selanjutnya terjadi pada masa 10 Juni 1991 yang materinya mencakup aturan pewarisan dan perwakafan yang diperuntukkan khusus bagi umat Islam. Berdasarkan Intruksi Presiden (Inpres) No. 1 Tahun 1991 KHI dikukuhkan sebagai rujukan resmi dalam bidang hokum material bagi para hakim di lingkungan Peradilan Agama di seluruh Indonesia.
KHI sebenarnya merupakan respon pemerintah terhadap timbulnya banyak kekhawatitan masyarakat akibat beragamnya keputusan Pengadilan Agama untuk suatu kasus yang sama. Keberagaman itu menjadi konsekuensi logis dari pandangan fiqih yang menjadi rujukan para hakim agama dalam memutuskan suatu perkara. Karena itu, muncul gagasan perlunya suatu hukum positif yang dirumuskan secara sistematis sebagai landasan rujukan bagi para hakim agama sekaligus sebagai langkah awal untuk mewujudkan kodifikasi hukum nasional.
Lagi-lagi, tujuannya adalah untuk unifikasi hukum. KHI mengandung dua hal, di satu sisi memudahkan kerja para hakim agama dan pihak-pihak lainnya yang akan mencari rujukan hukum, tetapi di sisi lain akan memangkas kreativitas dan upaya-upaya ijtihad dalam bidang hukum keluarga. Padahal, persoalan-persoalan baru terus bermunculan mengikuti dinamika masyarakat, seperti persoalan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sementara rujukan hukum tidak berubah, hal ini pada gilirannya menimbulkan kesulitan baru bagi para hakim itu sendiri di lapangan.
Jika perspektif budaya Indonesia, KHI dipandang kurang merepresentasikan kebutuhan dan keperluan umat Islam di Indonesia karena tidak digali secara seksama dari kearifan-kearifan lokal masyarakat di berbagai daerah, melainkan diangkut begitu saja dari fikih klasik yang bernuansa Arab.
Ketidakrelevanan fikih-fikih klasik ini disebabkan disusun dalam era, kultur, dan imajinasi sosial yang berbeda. Bahkan, disinyalir bahwa fikih klasik tersebut bukan saja tidak relevan dari sudut materialnya, namun juga bermasalah dari ranah metodologisnya. Misalnya, dari sudut definisi, fikih selalu dipahami sebagai “mengetahui hukum-hukum syara’ yang bersifat praktis yang diperoleh dari dalil-dalil tafshîlî, yaitu al-Qur`an dan al-Sunnah” [al-‘ilmu bi al-ahkâm al-syar’iyyah al-‘amaliyyah al-muktasab min adillatihâ al-tafshîliyyah].
Mengacu pada ta’rîf tersebut, kebenaran fikih menjadi sangat normatif, sehingga kebenaran fikih bukan didasarkan kepada seberapa jauh ia memantulkan kemaslahatan bagi umat manusia, melainkan pada seberapa jauh ia benar dari aspek perujukannya pada makna literal Al-Qur`an dan Sunnah.
Dari perspektif kesetaraan dan keadilan gender, KHI maupun Undang-undang Perkawinan (UUP) praktis menomorduakan suara perempuan. KHI menetapkan pandangan dominan dalam fiqih yang menempatkan perempuan sebagai “urutan kedua” setelah laki-laki, seperti dalam soal poligami dan kewajiban suami-isteri.
Padahal pihak-pihak yang menikah dan membentuk keluarga itu bukan hanya laki-laki, tapi juga perempuan. Mereka di mata Allah sama-sama kerja keras dan sama-sama dihargai pula. Tanpa diskriminasi, dan juga tanpa yang satu dilebihkan sedang yang lain direndahkan. Sementara fakta menunjukkan, kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga membuat kita prihatin.
Lalu apa langkah konkret yang harus kita lakukan untuk ini? Jawabannya adalah Sahkan RUU PKS…