BincangMuslimah.Com – Dalam agama Islam, pengambilan hukum berasal dari Al-Quran, Hadis, Ijma’, dan Qiyas. Proses pengambilan hukum dari tersebut kita kenal dengan akrab sebagai ijtihad. Ijtihad sendiri menurut ulama ushul fikih adalah pengerahan maksimal yang pakar fikih lakukan dalam mengolah dalil untuk menghasilkan hukum yang bersifat zhanni (praduga). Sedangkan pakar fikih tersebut memiliki julukan berupa mujtahid.
Syarat-syarat Menjadi Mujtahid
Untuk menjadi mujtahid, ada kriteria-kriteria yang harus terpenuhi. Imam Tajjuddin As-Subki menyebutkan ada 7 syarat untuk menjadi mujtahid, yakni: (1) Balig, hal ini karena menganggap orang yang belum menyandang status balig belum memiliki akal yang sempurna. (2) Memiliki kemampuan untuk mengolah dalil. (3) Faqih an-nafsi, yakni memiliki pemahaman yang baik atas maksud dari sebuah dalil. (4) Mengetahui dalil aqli. (5) Menguasai ilmu bahasa Arab yang meliputi nahwu, saraf, ma’ani, bayan, dan semacamnya. (6) Menguasai ilmu ushul fikih. (7) Menguasai apa saja yang berhubungan dengan ijtihad seperti Al-Quran dan hadis meskipun tidak menghafalnya.
Jika syarat menjadi mujtahid sudah terpenuhi, masih ada beberapa syarat lain agar ijtihad yang seorang mujtahid lakukan bisa di-i’tibar (dianggap); (1) Mengetahui ijma’ para ulama. (2) Mengetahui dalil yang menghapus dalil lain dan dalil yang telah dihapus. (3) Mengetahui hadis yang mutawatir dan ahad. (4) Mengetahui hadis yang valid dan tidak. (5) Mengetahui status atau kondisi perawi hadis. (6) Mengetahui latar belakang turunnya Al-Quran dan hadis. “Tajjuddin As-Subki, Jamu Al-Jawami’”
Nabi Juga Berijtihad
Memahami konteks ijtihad di atas, hal ini berlaku bagi orang yang ingin menggali hukum Islam. Lalu, apakah Nabi Muhammad yang notabenenya adalah orang yang langsung Allah utus untuk menyebarkan agama Islam juga melakukan ijtihad?
Menurut pendapat yang lemah, seorang nabi tidak boleh melakukan ijtihad. Hal ini karena seorang nabi secara yakin dapat mengetahui hukum-hukum dari wahyu yang diturunkan. Namun, hal ini dibantah dengan argumen bahwa penurunan wahyu atas hukum agama bukanlah kehendak Nabi.
Sedangkan pendapat yang kuat menurut Imam Zakariya Al-Anshari adalah Nabi boleh melakukan ijtihad dan Nabi pernah melakukannya. Sebagaimana firman Allah yang berbunyi;
مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُوْنَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِيْ الْأَرْضِ
Artinya: Tidak patut, bagi seorang Nabi mempunyai tawanan sebelum ia dapat melumpuhkan musuhnya di muka bumi. “Al-Anfal, ayat 67”
عَفَا اللهُ عَنْكَ لِمَ أَذِنْتَ لَهُمْ
Artinya: Semoga Allah memaafkanmu. Mengapa kamu mengapa kamu memberi izin (untuk mereka tidak ikut berperang). “At-Taubah ayat 43”
Pada surat Al-Anfal, Allah menegur Nabi yang mengambil tawanan dalam perang badar. Sedangkan dalam surat At-Taubah, teguran terjadi karena Nabi memberi izin kepada orang yang tampak jelas sifat munafiknya untuk tidak mengikuti perang. Menurut Imam Zakaria Al-Anshari, teguran tidak akan terjadi jika Nabi melakukan hal tersebut atas dasar wahyu. Maka dapat mengambil kesimpulan bahwa teguran Allah tersebut merupakan efek dari ijtihad yang Nabi lakukan.
Ijtihad Nabi Tidak Pernah Salah
Berbeda dengan para ulama yang memiliki potensi salah dalam berijtihad, menurut Imam Zakariya Al-Anshari, ijtihad yang dilakukan oleh nabi tidak pernah salah. Alasannya untuk menjaga status kenabiannya, karena jika kita menyatakan bahwa ada potensi salah dalam ijtihad beliau, sama halnya merusak status kenabian beliau.
Sedangkan menurut pendapat yang lemah, seorang Nabi bisa melakukan kesalahan dalam berijtihad, tetapi langsung mendapat teguran seperti dua ayat di atas. Namun, pendapat ini ditolak dengan argumen bahwa teguran dalam dua ayat di atas bukan karena Nabi salah dalam berijtihad, melainkan karena nabi meninggalkan hal yang lebih utama yakni tidak mengambil tawanan dan tidak memberikan izin untuk meninggalkan perang. “Zakariya Al-Anshari, Ghoyatul Wushul, halaman 157”
Rekomendasi






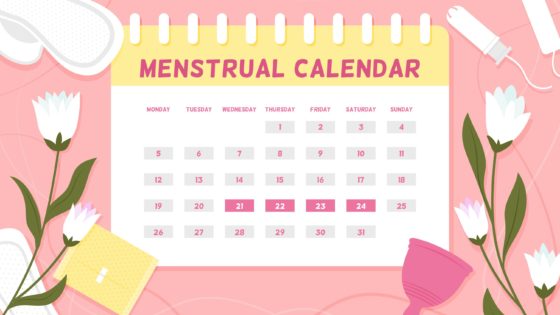
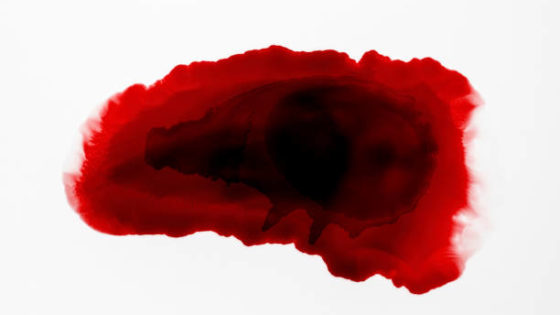







2 Comments