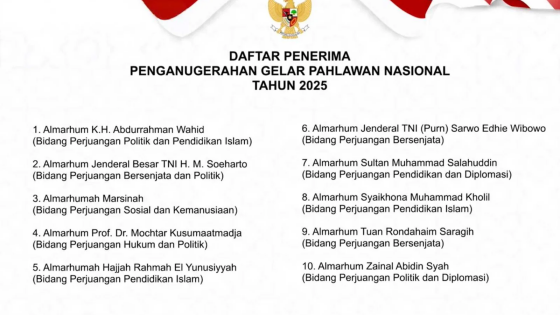BincangMuslimah.Com- Fikih muamalah merupakan salah satu konsep syariat Islam yang mengatur hubungan sosial-ekonomi antar manusia. Di dalam fikih muamalah, terdapat beberapa praktik dengan hukum dan implikasi yang berbeda. Di antaranya adalah praktik hiwalah dan wakalah.
Hiwalah dan wakalah merupakan praktik muamalah yang keduanya menerapkan adanya bentuk peralihan hak dari satu pihak kepada pihak lain. Akan tetapi, pada hakikatnya hiwalah dan wakalah merupakan 2 praktik muamalah yang berbeda. Lebih detailnya, berikut perbedaan antara hiwalah dan wakalah dalam konsep fikih muamalah.
Hiwalah
Secara etimologi hiwalah bermakna at-tahawwul yang berarti peralihan. Sedangkan secara terminologi syariat, hiwalah merupakan praktik pemindahan hak dari tanggungan pihak pertama (muhil) kepada pihak lain (muhal ‘alaih) atau transaksi peralihan hutang (Ibn Qasim, Fathul Qarib, [Beirut, Dar Ibn Hazm, 2005], 177).
Hiwalah di dalam Islam berlaku jika sudah memenuhi 4 syarat. Sebagaimana Abu Syuja’ menyebutkan:
وشرائط الحوالة أربعة أشياء رضا المحيل وقبول المحتال وكون الحق مستقرا في الذمة واتفاق ما في ذمة المحيل والمحال عليه في الجنس والنوع والحلول والتأجيل وتبرأ بها ذمة المحيل
“Syarat hiwalah ada 4. Yaitu, adanya kerelaan dari muhil (pihak pertama yang mengalihkan hutang), diterima oleh muhtal (pihak yang memiliki hak), hak yang masih berada dalam tanggungan, hak antara tanggungan muhil dan muhal ‘alaih (pihak lain yang mendapat peralihat tanggungan hutang) sama baik dari segi jenis, macam dan metode pembayarannya (kontan atau angsuran). Sedangkan tanggungan muhil terbebas ketika terjadi akad hiwalah” (al-Qhoyah al-Taqrib [Alim Kutub, 2004], 23-24)
Ketentuan Hiwalah
Berdasarkan keterangan ini, ketika hendak melakukan praktik hiwalah, seseorang harus memperhatikan beberapa aspek yang ada di dalam hiwalah dan mengetahui pihak-pihak yang terkait dengan praktik hiwalah.
Aspek tersebut maksudnya syarat yang harus terpenuhi dalam praktik hiwalah sebagaimana dalam penjelasan sebelumnya. Yakni harus adanya kerelaan dari pihak muhil, pihak muhtal menerima adanya peralihan hutang, hutang yang ada di dalam tanggungan muhil atas muhtal dan hutang muhal ‘alaih atas muhil merupakan hutang yang tetap (masih ada/ bukan sekedar rencana akan berhutang), dan antara hutang yang menjadi tanggungan muhil dan muhal ‘alaih harus sama baik dalam jenis, macam ataupun metode pembayarannya.
Sedangkan pihak-pihak yang teribat di atas merupakan pihak-pihak yang terlibat di dalam praktik hiwalah yang meliputi:
Pertama, muhil. Muhil merupakan pihak pertama yang melakukan peralihan hutang. Dalam praktiknya, muhil sejatinya memiliki hutang kepada pihak muhtal yang kemudian tanggungan tersebut dialihkannya kepada muhal ‘alaih. Sehingga ketika terjadi hiwalah, muhil tidak memiliki tanggungan lagi kepada muhtal dan tidak memiliki hak apapun atas muhal ‘alaih.
Kedua, muhal ‘alaih. Muhal ‘alaih merupakan istilah yang diperuntukkan bagi pihak yang memiliki tangggungan atau hutang kepada muhil. Ketika terjadi hiwalah, tanggungan pihak ini yang seharusnya diberikan kepada muhil beralih kepada muhtal.
Ketiga, muhtal. Muhtal merupakan pihak yang memiliki hak/piutang dari muhil. (Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah, [Beirut: Dar Kutub ‘Arabi, 1997], 3/211)
Contoh Praktik Hiwalah
Praktik hiwalah adalah praktik muamalah yang melibatkan 3 pihak dan 2 hutang. Contohnya Hikam memiliki hutang 10.000 kepada Ahmad. Di sisi lain, Zaid memiliki hutang 10.000 kepada Hikam. Ketika tiba waktunya jatuh tempo, Hikam ingin mengalihkan hutangnya kepada Zaid (melakukan akad hiwalah). Kemudian, Hikam berkata kepada Ahmad, “Aku mengalihkan hutangku yang menjadi hakmu kepada Zaid.” (Fiqih ‘ala Mazhabil ‘Arba’ah, [Beirut: Dar Kutub Ilmiyah, 2003], 3/185)
Contoh praktik pengalihan hutang di atas merupakan contoh praktik hiwalah yang dibenarkan. Karena di dalam contoh tersebut sudah memenuhi 4 syarat hiwalah. Pada contoh tersebut, Hikam yang merupakan muhil rela untuk mengalihkan piutangnya yang ada pada Zaid untuk diberikan kepada Ahmad sebagai pelunasan hutang Hikam. Di samping itu, Ahmad juga menerima peralihan hutang tersebut, dan hutang milik Hikam dan Zaid memiliki kadar yang sama yaitu 10.000.
Dengan demikian, akad hiwalah yang dilakukan antara Hikam, Ahmad dan Zaid adalah praktik hiwalah yang sah. Konsekuensinya, Hikam terbebas dari hutangnya kepada Ahmad dan tidak memiliki ha katas Zaid. Sedangkan Zaid tidak lagi memiliki hutang kepada Hikam, melainkan harus dibayarkan kepada Ahmad.
Wakalah
Secara etimologi, wakalah bermakna tafwidh yang berarti memberikan kuasa. Sedangkan menurut terminologi syariat, wakalah merupakan praktik penyerahan kuasa terhadap sesuatu yang pelaksanaannya bisa dengan pengganti, dari seseorang kepada orang lain. Orang lain ini nantinya akan menempati posisi pihak pertama yang memberikan kuasa untuk melakukan sesuatu tersebut. Praktik ini juga terkenal sebagai praktik pemberian mandat/wewenang/delegasi (Ibn Qasim, Fathul Qarib, [Beirut, Dar Ibn Hazm, 2005], 183).
Kebolehan praktik wakalah ini untuk setiap tindakan yang bisa mewakilkan orang lain sebagai pengganti. Seperti jual beli, hibah, gadai, akad nikah dan sebagainya. Dengan catatan, seseorang yang memberikan kuasa (muwakkil) memang memiliki wewenang atas tindakan tersebut dan si wakil memiliki kecakapan untuk melakukan tindakan yang diwakilkan.
Ketentuan Wakalah
Berdasarkan keterangan tersebut, terdapat beberapa hal yang harus terpenuhi ketika melakukan praktik wakalah. Yaitu, syarat yang berkaitan dengan bentuk (shighot) akad, pelaku wakalah (wakil dan muwakkil) dan sesuatu/tindakan yang bisa diwakilkan.
Pertama, syarat shighot akad wakalah. Ketika mengucapkan shighat tawkil, seseorang yang memberikan wewenang (muwakkil) harus menunjukkan kerelaannya kepada wakil (orang yang menerima perwakilan) untuk bisa mewakilinya melakukan suatu tindakan. Selain itu, muwakkil tidak boleh menggantungkan perwakilannya. Dengan kata lain, perwakilan harus terjadi ketika akad tanpa menunggu apapun.
Kedua, syarat pelaku wakalah. Di dalam wakalah, melibatkkan 2 pihak yaitu pihak yang bertindak sebagai muwakkil (orang yang memberi wewenang) dan pihak wakil (orang yang menerima mandat). Saat melakukan praktik wakalah, seorang muwakkil harus memiliki wewenang utuh atas tindakan yang akan ia wakilkan dan harus memiliki kecakapan hukum dalam bertindak. Sedangkan syarat orang yang bertindak sebagai wakil ialah memiliki kecakapan hukum karena posisi wakil adalah sebagai pengganti muwakkil sehingga sepatutnya memiliki kecakapan yang setara dalam tindakan hukum.
Ketiga, syarat sesuatu/tindakan yang diwakilkan. Tindakan yang bisa diwakilkan adalah sesuatu yang dibolehkan di dalam syariat Islam, dimiliki oleh muwakkil, diketahui oleh wakil maupun muwakkil, tindakan bukan berupa meminta pinjaman/hutang, dan tindakan yang diwakilkan harus bisa digantikan oleh orang lain. (Wahbah al-Zuhaily, Fiqih Islamy wa adillatuhu, [Damaskus: Darul Fikr, 2011], 5/4062-4065)
Contoh Praktik Wakalah
Sebagaimana dalam pembahasan sebelumnya, bahwa wakalah hanya dibenarkan untuk sesuatu yang bisa untuk diwakilkan. Sedangkan selainnya seperti sumpah dan ikrar maka tidak boleh untuk diwakilkan. Contoh praktik wakalah misalnya si A memiliki rumah untuk dijual. Karena satu dan lain hal, si A meminta si B untuk menjualkan rumahnya seraya berkata kepada B, “Aku mewakilkan kepadamu untuk menjual rumahku.” (Zainuddin al-Malibary, Fathul Mu’in, [Beirut, Dar Ibn Hazm, 2009], 361)
Pada contoh ini, si A sebagai muwakkil yang memiliki wewenang untuk menjual rumah memberikan wewenangnya kepada B yang memiliki kecakapan hukum sebagaimana si A. Selain itu si A juga menjelaskan tindakan apa yang ia izinkan untuk dilakukan oleh si B. Sehingga praktik ini masuk kategori sebagai praktik wakalah yang benar.
Perbedaan Hiwalah dan Wakalah
Hiwalah dan wakalah merupakan 2 praktik yang berbeda di dalam muamalah. Dalam praktik hiwalah, terjadi peralihan tanggungan antara muhil kepada muhal ‘alaih. Implikasinya, saat terjadi praktik ini, muhil tidak lagi memiliki tanggungan ataupun hak kepada siapapun. Sedangkan wakalah merupakan praktik peralihan wewenang antara muwakkil kepada wakil. Akan tetapi, pada praktik ini, wewenang wakil terhadap sesuatu atau sebuah tindakan hanya berlangsung selama terjadinya perwakilan saja. Dengan kata lain, suatu wewenang pada hakikatnya tetap menjadi hak dari muwakkil.
Baik hiwalah ataupun wakalah merupakan praktik muamalah yang keduanya memiliki manfaat dalam mempermudah hubungan sosial-ekonomi manusia. Namun, untuk melakukan praktik ini secara benar dan sah secara syariat tetap harus memenuhi syarat dan ketentuan ketetapan yang berlaku.
Rekomendasi