BincangMuslimah.Com- Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) di Indonesia sering menjadi kontroversi karena dianggap tumpul dalam melindungi masyarakat dan tajam dalam mengkriminalisasi ekspresi. Hal ini berakar pada sifatnya yang terlalu prosedural dan teknis (legalistik) tanpa landasan etika yang kuat. Terutama untuk membatasi penyalahgunaan pasal-pasal seperti pencemaran nama baik.
Masalah utamanya adalah UU ini terlalu berorientasi pada sanksi teknis tanpa memiliki jiwa etis yang mendalam dari kearifan lokal. Maksudnya, UU ITE seringkali fokus pada pelanggaran teknis dan sanksi pidana yang keras, tanpa mempertimbangkan niat (motif), konteks sosial. Juga mempertimbangkan dampak nyata dari suatu unggahan atau ekspresi digital terhadap kemaslahatan umum (kesejahteraan sosial).
Di sinilah Maqashid Syariah—tujuan-tujuan utama dari pensyariatan Islam—dapat diproyeksikan sebagai kerangka filosofis untuk memperkuat dan memanusiakan hukum digital. Maqashid syariah berpusat pada perlindungan terhadap lima hal mendasar (al-Dharuriyat al-Khamsah): Agama (Din), Jiwa (Nafs), Akal (Aql), Keturunan (Nasl), dan Harta (Mal). Dengan memproyeksikan kelima tujuan ini ke dalam UU ITE, kita tidak hanya memperkuat dasar hukumnya. Tetapi juga membangun etika digital Islam yang kokoh.
pertama: Perlindungan Agama (Hifzh al-Din): Melawan Penodaan Digital yang Disengaja
Hifzh al-Din adalah tujuan primer maqashid syariah, yaitu melindungi keyakinan dan praktik keagamaan. Dalam konteks digital, prinsip ini harus menggarisbawahi perbedaan antara kritik akademis yang sah terhadap praktik keagamaan dan penodaan yang disengaja (blasphemy) yang berniat merendahkan serta memicu konflik.
Penerapan Maqashid: Prinsip Hifzh al-Din menuntut UU ITE untuk mendefinisikan batas antara kebebasan berekspresi dan ujaran kebencian yang menargetkan simbol suci agama. Fokusnya harus bergeser dari sekadar ‘merasa tersinggung’ ke ‘tindakan terencana yang merendahkan dan memicu permusuhan’ berdasarkan SARA. Hal ini harus sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang ada.
Contoh Kasus: Seorang pengguna media sosial membuat meme vulgar yang secara langsung mengolok-olok praktik ibadah suatu agama atau menistakan simbol-simbol sucinya (misalnya, Al-Qur’an, Ka’bah, atau salib). Tindakan ini melanggar Hifzh al-Din karena secara terang-terangan dan disengaja merusak kesakralan agama dan memicu kemarahan umat, yang berpotensi mengganggu keamanan publik. Sehingga hukum UU ITE yang berbasis maqashid harus mempertegas bahwa konten semacam ini merupakan delik pidana berat. Selain itu, undang-undang tersebut juga harus membedakannya dengan diskusi teologis yang mungkin kontroversial tetapi dilakukan dengan niat baik untuk tujuan akademik atau dakwah.
kedua: Perlindungan Jiwa (Hifzh al-Nafs): Melawan Cyberbullying dan Trauma Digital
Dalam ranah digital, jiwa manusia seringkali terluka parah oleh perundungan dan serangan siber. UU ITE saat ini cenderung hanya fokus pada pencemaran nama baik, tetapi kurang peka terhadap dimensi trauma psikologis dan kesehatan mental korban.
Penerapan Maqashid: Prinsip Hifzh al-Nafs (perlindungan jiwa) menuntut hukum tidak hanya mengkriminalisasi pelaku, tetapi juga mewajibkan pemulihan psikologis dan rehabilitasi korban cyberbullying secara tegas dalam regulasi.
Contoh Kasus: Seorang remaja menjadi korban doxing (penyebaran data pribadi) hingga mengalami depresi berat. UU ITE yang berbasis maqashid harusnya tidak hanya menjerat pelaku dengan pasal pencemaran, tetapi juga memaksa platform digital untuk menghapus konten perundungan tersebut dengan cepat (perlindungan preventif) dan memberikan kompensasi ganti rugi yang mencakup biaya pemulihan trauma korban, bukan sekadar denda material.
Ketiga: Perlindungan Akal (Hifzh al-Aql): Melawan Disinformasi dan Deepfake.
Hifzh al-Aql adalah perlindungan terhadap akal sehat dan kemampuan berpikir jernih. Di era post-truth, akal masyarakat dirusak oleh hoaks, disinformasi, dan manipulasi digital canggih seperti deepfake.
Penerapan Maqashid: Prinsip ini menuntut pertanggungjawaban yang lebih berat bagi penyebar disinformasi yang terstruktur dan masif, karena merusak nalar kolektif dan memicu konflik sosial. Ini harus menjadi pasal khusus yang berbeda dari sekadar berita bohong biasa.
Contoh Kasus: Pembuatan dan penyebaran video deepfake seorang tokoh agama atau tokoh politik yang seolah-olah mengeluarkan pernyataan kontroversial. Jika mengukur ini dengan maqashid, perbuatan ini tidak hanya melanggar UU ITE, tetapi juga melanggar Hifzh al-Aql karena secara sengaja merusak pola pikir kebenaran masyarakat. Hukuman harus berlipat ganda karena dampaknya bukan hanya pada individu, tetapi pada stabilitas nalar publik.
Keempat: Perlindungan Keturunan (Hifzh al-Nasl): Menjaga Moralitas dan Keluarga Digital
Hifzh al-Nasl secara tradisional berarti menjaga garis keturunan dan moralitas. Dalam konteks digital, hal ini meluas menjadi perlindungan terhadap integritas moralitas publik, keluarga, dan anak di dunia maya. Prinsip ini mendasari upaya melawan konten pornografi, eksploitasi anak, dan perusakan nilai-nilai keluarga melalui platform digital.
Penerapan: Hifzh al-Nasl dalam konteks tradisional syariah adalah perlindungan terhadap garis keturunan, integritas pernikahan, dan moralitas sosial. Dalam dunia digital, prinsip ini bertransformasi menjadi perlindungan terhadap integritas moralitas digital masyarakat. Khususnya anak-anak, dari ancaman yang merusak masa depan mereka. Penerapan Hifzh al-Nasl menuntut pergeseran fokus dalam UU ITE, dari sekadar penindakan pascakejadian (menghukum pelaku) menjadi pencegahan proaktif (menciptakan lingkungan digital yang aman).
Contoh Kasus: Sebuah akun media sosial atau situs web secara aktif menyebarkan materi pornografi anak (child pornography) atau promosi prostitusi online secara terorganisir. Tindakan ini merupakan pelanggaran paling serius terhadap Hifzh al-Nasl. Karena secara langsung merusak masa depan keturunan (anak-anak), menghancurkan moralitas keluarga, dan memfasilitasi perbuatan nista. Sehingga UU ITE dengan dasar Hifzh al-Nasl harus menjatuhkan hukuman maksimal. Tidak hanya berupa kurungan penjara, tetapi juga denda yang sangat besar dan pemblokiran permanen terhadap semua infrastruktur digital yang terlibat. Prinsip ini juga mendorong kerjasama lintas negara yang lebih kuat dalam melacak dan menangkap predator siber.
Kelima: Perlindungan Harta (Hifzh al-Mal): Menjaga Data dan Privasi.
Meskipun secara tradisional Hifzh al-Mal adalah perlindungan terhadap aset fisik, di era digital, data pribadi adalah harta yang paling berharga. Kebocoran dan penyalahgunaan data adalah bentuk pencurian modern.
Penerapan Maqashid: Prinsip ini menegaskan bahwa privasi dan keamanan data adalah hak fundamental yang harus dilindungi secara hukum. UU ITE harus memberikan sanksi yang sangat berat kepada entitas, baik pemerintah maupun swasta, yang lalai atau sengaja membocorkan data masyarakat.
Contoh Kasus: Kasus kebocoran data jutaan pengguna oleh sebuah perusahaan teknologi. Sanksi yang ideal, dengan landasan Hifzh al-Mal. Harusnya tidak hanya berupa denda administratif, tetapi juga pembekuan operasional. Bahkan pencabutan izin bagi perusahaan yang terbukti tidak serius dalam melindungi ‘harta’ digital penggunanya.
Dari penjelasan di atas dapat kita simpulkan bahwa penerapan Maqashid Syariah sebagai kerangka filosofis dalam hukum digital bertujuan untuk menggeser orientasi hukum. Yakni dari sekadar sanksi teknis ke perlindungan nilai-nilai fundamental yang universal, atau sebagai Lima Pilar Utama Maqashid Syariah (al-Dharuriyyat al-Khams). Sehingga Dengan menjadikan Maqashid Syariah sebagai jiwa etis. Hukum digital di Indonesia akan berubah dari sekadar alat untuk menghukum menjadi instrumen untuk melindungi nilai-nilai esensial kemanusiaan. Juga memastikan bahwa penggunaan teknologi untuk mencapai keadilan, kesejahteraan, dan harmoni sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Semoga bermanfaat. Wallahu A’lam.
Rekomendasi




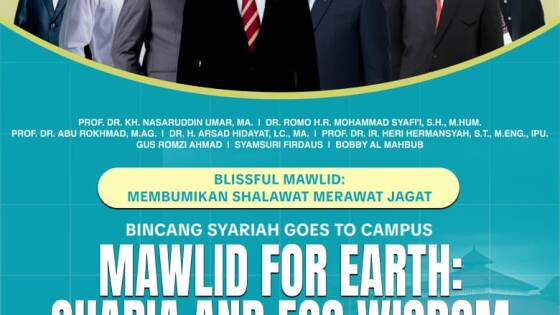






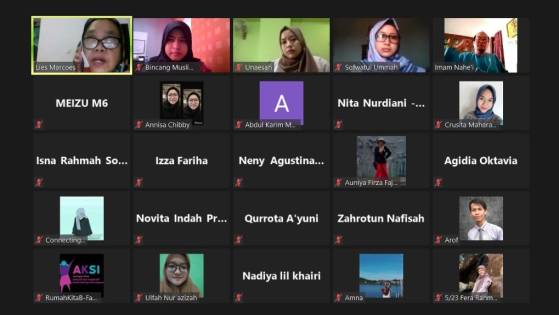

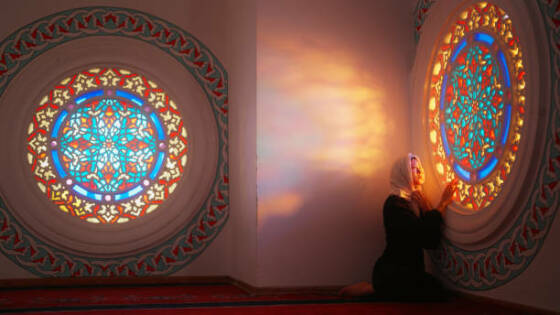


5 Comments